Ada masa-masa dalam hidup yang tidak hanya meninggalkan jejak, tapi menggurat luka. Luka yang tidak terlihat oleh mata, tidak terdeteksi oleh alat medis mana pun, tapi terasa menyakitkan setiap kali seseorang mengucap kata yang memicu ingatan itu, atau ketika malam datang terlalu sunyi, dan pikiran mulai memutar kembali kejadian yang seharusnya sudah lama berlalu. Trauma bukan sekadar kenangan buruk. Ia seperti kabut yang diam-diam menyusup ke dalam hari-hari, mengganggu tidur, mengacaukan napas, kadang menjelma menjadi rasa bersalah tanpa alasan, rasa takut yang tidak jelas asalnya, atau bahkan kemarahan pada diri sendiri.
Menghadapi trauma bukan tentang melupakannya, bukan pula memaksakan diri untuk terlihat kuat di depan orang lain. Kadang, menghadapi trauma adalah menerima bahwa ada bagian dari hidup yang tidak akan pernah kembali utuh seperti dulu. Tidak apa-apa. Menyadari bahwa kamu terluka adalah langkah pertama. Bahwa kamu masih bisa bangun, meski pelan, meski gemetar, adalah bukti bahwa kamu masih hidup. Dan hidup, dengan segala ketidaksempurnaannya, masih memberimu ruang untuk bernapas.
Ada kalanya tubuh lebih cepat merespons dari pada logika. Tiba-tiba jantung berdebar, telapak tangan berkeringat, atau kamu merasa sesak di tengah keramaian tanpa sebab yang jelas. Itu bukan kelemahan. Itu tubuhmu sedang mengingat—dan itu adalah bagian dari proses. Tidak ada jalan pintas untuk sembuh. Bahkan waktu pun tidak benar-benar menyembuhkan, ia hanya memberi jarak agar kamu bisa melihat luka itu tanpa rasa perih yang sama.
Perjalanan menghadapi trauma bukan soal membuktikan sesuatu kepada dunia, tapi tentang menemukan kembali dirimu yang tercecer di antara pecahan kenangan itu. Kadang, kamu akan merasa baik-baik saja, lalu tiba-tiba runtuh lagi. Itu wajar. Pemulihan bukan garis lurus, tapi siklus. Ada kemajuan, ada kemunduran, ada hari di mana kamu bisa tertawa tanpa merasa bersalah, dan ada hari di mana air mata turun tanpa peringatan.
Yang penting adalah terus berjalan. Sekalipun itu berarti hanya bisa bertahan dari satu hari ke hari berikutnya. Sekalipun kamu tidak yakin ke mana arahmu. Kadang yang kamu butuhkan bukan solusi, tapi pelukan. Bukan nasihat, tapi ruang untuk menangis tanpa dihakimi. Mungkin kamu tidak akan pernah menjadi "dirimu yang dulu"—dan itu tidak apa-apa. Karena bisa jadi, kamu akan menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih lembut, lebih mengerti bahwa luka orang lain juga tak selalu terlihat.
Dan di suatu titik nanti, ketika kamu menengok ke belakang, kamu akan sadar: kamu tidak sepenuhnya hancur. Kamu bertahan. Kamu mengarungi badai yang hanya kamu yang tahu seberapa kencangnya. Kamu tetap di sini—dan itu adalah bentuk kemenangan yang tidak perlu diumumkan, tapi pantas untuk dihargai.
Luka yang tidak terlihat sering kali lebih sulit dipahami, bahkan oleh diri sendiri. Ada hari-hari di mana kamu merasa seperti orang asing di tubuhmu sendiri. Kejadian yang sudah lama berlalu tetap hadir, seolah waktu tak pernah benar-benar bergerak. Suara-suara dalam kepala menyalahkanmu, menyuruhmu untuk melupakan, tapi tidak ada tombol yang bisa ditekan agar semuanya lenyap. Dan mungkin yang paling melelahkan dari trauma adalah bahwa kamu tidak bisa menjelaskan semuanya kepada orang lain tanpa merasa seakan-akan sedang membuka luka di depan panggung yang terlalu terang.
Namun dalam semua itu, pelan-pelan kamu belajar bahwa kamu tidak harus menjelaskan. Kamu tidak harus membuat semua orang mengerti. Yang penting adalah kamu mengerti dirimu sendiri, seiring waktu. Kamu mulai mengenali pemicunya—lagu tertentu, aroma tertentu, ucapan tertentu—dan kamu belajar mengambil jarak. Kamu mulai tahu kapan harus memberi ruang untuk menangis, kapan harus menenangkan diri dengan secangkir teh hangat, dan kapan kamu cukup duduk diam tanpa menghakimi emosi yang datang.
Kamu pun belajar bahwa tidak semua orang aman untuk menjadi tempat berbagi, dan itu membuatmu sedikit lebih hati-hati. Tapi bukan berarti kamu berhenti percaya pada dunia. Kepercayaan yang pernah hancur perlahan tumbuh lagi, meski dengan bentuk dan batas yang berbeda. Ada orang-orang yang datang tidak untuk memperbaiki, tapi hanya untuk menemani. Mereka duduk di sebelahmu dalam diam dan tidak mendesakmu untuk cepat pulih. Mereka tahu bahwa hadir saja sudah cukup berarti. Dan kehadiran seperti itu adalah obat yang paling sunyi tapi paling dalam.
Malam-malam panjang masih ada, tapi kamu tidak lagi merasa sendirian di dalamnya. Kadang kamu menulis, kadang kamu hanya mendengarkan lagu-lagu yang menyentuh sesuatu yang bahkan tidak bisa kamu sebutkan namanya. Tapi dari semua itu, kamu mulai melihat: trauma tidak mencuri semuanya darimu. Ia memang mengubahmu, tapi ia juga membuatmu lebih sadar, lebih peka, lebih mampu menghargai momen-momen kecil yang dulu mungkin terlewat. Sinar matahari di pagi hari, angin yang menggerakkan tirai, tawa yang lepas sesekali—hal-hal sederhana seperti itu menjadi penanda bahwa hidup masih bisa terasa hangat, meski tidak sempurna.
Dan suatu hari, tanpa kamu sadari, kamu akan menoleh ke belakang dan menemukan bahwa rasa sakit itu tak lagi menakutkan seperti dulu. Ia tetap ada, tapi tidak lagi mendikte langkahmu. Kamu mungkin masih membawa bekasnya, tapi bukan sebagai beban—melainkan sebagai bagian dari kisahmu yang tak perlu disembunyikan.
Kamu bukan trauma itu. Kamu adalah seseorang yang sedang tumbuh kembali dari reruntuhan. Dan itu, dalam segala sunyinya, adalah kekuatan yang tak bisa dipatahkan.
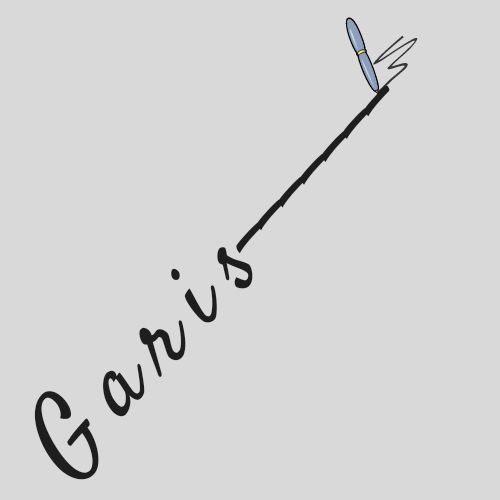





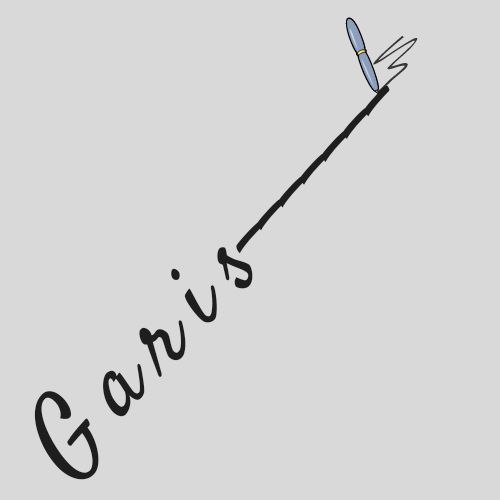
0 Komentar